Jurnalis juga Perlu Peringati May Day
Sebelumnya,
selamat hari buruh.
Relasi
hubungan industri yang dibangun dengan sistem pengupahan, mengakibatkan para
pekerja disebut dengan buruh. Ini yang menguatkan sebagian besar pandangan
kami, terutama yang berada di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyatakan
jurnalis juga buruh dari sistem
industri, tidak lain sebuah sistem industri media. Tentu dengan berbagai
persoalan yang masih dialaminya.
Berangkat
dari perdebatan apakah jurnalis juga buruh atau bukan. Ada baiknya, kita
menengok bagaimana kelas-kelas pekerja atau dikenal dengan buruh melakukan
pergerakkannya sejak dulu di Indonesia. Peringatan may day atau dikenal dengan
hari buruh internasional sebenarnya bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia.
Hanya saja, pergolakan politik dalam dasawarsa sebelumnya, membuatnya harus “dilenyapkan”
dengan stigma bahwa peringatan hari buruh indentik dengan paham yang
mati-matian dimusuhin di Indonesia.
Untuk
lebih mudah, menengok pasang surut peringatan hari buruh di Indonesia, maka
fasenya bisa dibagi sebelum kemerdekaan, setelah dan saat ini. Setelah
kemerdekaan, perjuangan buruh di Indonesia sedikit menuai hasil, yakni lahir
peraturan mengenai tunjangan hari raya sebagai hak buruh. Dari berbagai sumber
menyebutkan pada tahun 1946, atau pada kabinet Syahrir, may day diperbolehkan
yang dijamin dalam UU nomor 12 tahun 1948 yang menyatakan pada tanggal tersebut
pekerja (buruh) dibebaskan bekerja.
Tentu,
euforia kala itu berkembang menjadi demontrasi yang meluas, sehingga akhirnya
19 Mei terjadi mogok besar menuntut perbaikan upah pekerja. Dua tahun
setelahnya, perjuangan serikat buruh yang telah meluas dengan perjuangan
peraturan mengenai tunjangan hari raya. Meski harus menunggu dua tahun, pada
1954, pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan yang dikenal dengan persekot
hari raya melalui surat edaran berjudul hadiah lebaran dan Permen nomor 1/1961,
menetapkan tunjangan tersebut sebagai hak buruh.
Menulis
perjuangan buruh di Indonesia memang hal menarik. Tidak hanya pada setelah
kemerdekaan, para pendahulu juga sudah mengenalkan hari buruh internasional
sebagai bagian dari perjuangan kelas pekerja di Indonesia.
Pada
tahun 1921 misalnya, HOS Tjokroaminoto bersama dengan Soekarno berpidato
lantang jika mereka mewakili kelas buruh Indonesia. Dua tahun setelahnya,
Semaun yang menjadi Ketua pertama PKI juga menyerukan agar buruh bersatu dan
mogok menuntut kesejahteraan lebih baik. Meski partai ini kandas juga di tahun
1926.
Kembali
menelisik perjuangan buruh di Indonesia, yang pasang surut mencatat tragedi
suram saat hari buruh dihapuskan pada sekitar tahun 1967- atau masa Orde baru. Meski
demikian, perjuangan buruh masih berlangsung meski harus mendapatkan
represivitas dari penguasa. Salah satunya, mogok pekerja perusahaan di Surabaya
yang menyebabkan pekerja Marsinah tewas di tahun 1993.
Potret
suram itu berubah saat setelah reformasi, saat presiden BJ Habibie memperbaiki
konvensi ILO tentang kebebeasan pers berserikat buruh dan dikeluarkannya UU
nomo 21 tahun 2000 (https://beritagar.id/artikel/berita/sejarah-hari-buruh-di-indonesia) yang diikuti oleh UU nomor 21
tahun 2000.
Saat itu, aksi-aksi buruh masih terpusat di beberapa kota besar di
Indonesia, dan baru pada 2014, 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur nasional.
Meski pada tanggal itu, para pekerja diliburkan dengan rutinasnya, sekelumit
permasalahan pekerja masih menyelimuti, termasuk pada jurnalis.
Tradisi untuk memperingati may day digelar oleh sebagian besar jurnalis
dengan isu-isu ketenagakerjaan yang terus diperjuangan.
Sebagai pekerja (buruh), jurnalis masih dibayangi dengan persoalan yang
sama dengan pekerja lainnya, misalnya sistem kerja kontrak yang berkepanjangan,
tidak terpenuhinya standar gaji atau upah sebagai dengan upah minimum regional
(UMR), hingga persoalan pemutusan hubungan kerja sepihak yang tentu merugikan
pekerja.
Berangkat dari itu, AJI makin konsen bahwa jurnalis atau pekerja masih
dihantui permasalahan ketenagakerjaan yang kian kompleks.Misalnya saja, selain
status ketenagakerjaan atau sistem kerja lepas yang melepaskan perusahaan dari
kewajiban jaminan sosial, seperti kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan,
pembentukan serikat kerja juga sangat minim.
Catatan AJI, jumlah serikat kerja yang dibangun oleh perusahaan media,
barulah 25 serikat, namun Dewan Pers sudah merilis bahwa jumlah media di
Indonesia mencapai 47.000 unit. Perkembangan unit media, ternyata tidak sejalan
dengan upaya perlindungan terhadap jurnalis. Keberadaan serikat pekerja sangat
penting dalam memperkuat posisi para pekerja dalam pengambilan kebijakan di
sebuah unit perusahaan. Jika keberadaannya pun tidak didukung, atau malah tidak
dibangun, maka pekerja akan semakin sulit memperoleh kesejahteraan.
Perbandingan jumlah serikat dan unit media yang terus berkembang, merupakan
perbandingan yang sangat jomplang bagi perjuangan buruh mendapatkan
kesejahteraan. Belum lagi, pemenuhan hak bagi jurnalis perempuan, seperti cuti
haid, melahirkan dan tersedianya ruang laktasi di perusahaan masih belum banyak
dipenuhi. Belum lagi, ancaman jurnalis perempuan, karena kekerasan seksual juga
lebih tinggi.
Sekelumit persoalan yang dihadapi jurnalis ini, diperlengkap dengan ancaman
kekerasan yang makin sering dialami jurnalis dalam menjalani profesinya. AJI
Indonesia mencatat pada tahun 2018, kekerasan terhadap jurnalis meningkat dan
dengan masih didominasi oleh kekerasan fisik, dan lainnya. Jumlah kekerasan
yang dialami jurnalis Indonesia di tahun tersebut sudah lebih dari 60 kejadian.
Tak cukup sampai di situ, perkembangan teknologi, yang mengharuskan media
“beradaptasi” juga masih mengancam kepastian ketenagakerjaan bagi jurnalis di
Indonesia. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) menangani 11 kasus
ketenagakerjaan di tujuh media perusahaan. Dari jumlah itu, lima disebabkan
oleh berhentinya operasional media cetak (senjakala media cetak). Perselisihan
kasus ketenagakerjaan biasanya pada pola yang sama, yakni perusahaan tidak
mampu lagi bersaing akibat perkembangan teknologi tersebut. Sebaiknya,
perusahaan membangun sistem (manajemen) yang lebih mampu menghadapi tuberlensi
media sehingga tidak berimbas pada tenagakerjannya.
Hingga akhirnya, mungkin bukan kata sekelumit lagi yang dipakai dalam
menggambarkan permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi jurnalis saat ini, namun
lebih pada “semakin menumpuk,”. Karena itu, kesadaran untuk berserikat dan
menguatkan barisan juga menjadi bagian penting yang harus dipupuk oleh para
jurnalis agar makin kuat dan sejahtera. Bukanlah, saat jurnalis “sehat” maka
perusahaan akan semakin maju dan kuat.
Salam Jurnalis.
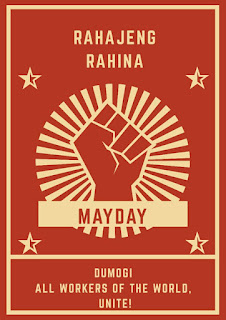
Komentar
Posting Komentar